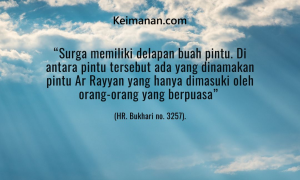Tafsir Surat At-Taubah Ayat 34: Larangan Menimbun Harta, Makna Iktinaz & Hikmah Keadilan Sosial

Keimanan – #Dalam #Islam, #harta #tidak #sekadar #untuk #dikumpulkan, #tetapi #harus #berfungsi #sebagai #sarana #kemaslahatan #umat. Surat At-Taubah Ayat 34 memberikan peringatan tegas tentang penimbunan kekayaan (iktinaz) yang dapat menggangu keseimbangan ekonomi dan sosial. Tafsir ayat ini tidak hanya menjelaskan larangan menimbun emas dan perak, tetapi juga memberikan pelajaran tentang pentingnya zakat, distribusi kekayaan, serta tanggung jawab sosial dalam perspektif Islam.
Baca juga; Surat Al-Jumu’ah: Keutamaan, Asbabun Nuzul, Kandungan Ayat, dan Perintah Sholat Jum’at Lengkap

Dalam sejarah Islam, praktik iktinaz atau menimbun kekayaan ini ini tidak hal baru. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sudah ada beberapa sahabat yang menimbun emas dan perak, yang saat itu berfungsi sebagai alat tukar dan pembayaran masyarakat. Ada 2 alat tukar yang masyhur zaman Nabi, yaitu dinar, sebagai alat terbuat dari emas. Lalu dirham terbuat dari perak.
Lebih jauh, praktik iktinaz, dalam konteks klasik, istilah ini merujuk pada orang yang menyimpan emas dan perak di tempat tersembunyi, enggan mengeluarkan zakat atau membantu orang lain. Sementara dalam konteks modern, iktinaz bisa tampil dalam berbagai bentuk; rekening bank yang terus membengkak tanpa pernah mengalir untuk kemaslahatan, gudang yang penuh dengan stok barang yang sengaja tidak diedarkan demi menunggu harga naik, hingga kepemilikan aset besar yang dibiarkan menganggur.
Membiarkan harta ini menganggur sama saja menahan peredaran ekonomi, menghambat kesejahteraan sosial. Lebih jauh dari itu, akan menimbulkan monopoli harga. Larangan iktinaz ini tercantum dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 34:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٤
yâ ayyuhalladzîna âmanû inna katsîram minal-aḫbâri war-ruhbâni laya’kulûna amwâlan-nâsi bil-bâthili wa yashuddûna ‘an sabîlillâh, walladzîna yaknizûnadz-dzahaba wal-fidldlata wa lâ yunfiqûnahâ fî sabîlillâhi fa basysyir-hum bi‘adzâbin alîm
Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.“
Pengertian Iktinaz
Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kanz atau iktinaz dalam ayat 34 tersebut? Imam Thabari dalam Jami‘ul Bayan menjelaskan ulama berbeda pendapat tentang definisi “menimbun harta/iktinaz” dalam surat At-Taubah ayat 34 itu.
Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, perbedaan pendapat ulama yang dimaksud iktinaz di atas, penting untuk dicatat satu hal: meski berbeda dalam definisi, semua ulama sepakat bahwa menimbun harta yang seharusnya digunakan untuk zakat atau kepentingan sosial itu salah dan tercela. Jadi, meski makna kanz/iktinaz bisa berbeda-beda menurut ulama, semuanya setuju: harta harus digunakan dengan bijak dan sesuai amanah, bukan untuk ditimbun karena keserakahan atau mengabaikan kewajiban sosial.
Baiklah, mari kita bahas perbedaan pendapat ulama, tentang apa itu iktinaz atau menimbun harta dalam ayat 34 tersebut. Pertama, menurut Imam Thabari, sebagaimana mengutip riwayat Abdullah bin Umar, yang dimaksud iktinaz atau menimbun harta adalah ketika seseorang memiliki harta (emas dan perak) yang sudah wajib dizakati, tetapi tidak mau mengeluarkan zakatnya.
Inilah maksud iktinaz dalam ayat 34 Surat At-Taubah itu, yakni orang yang enggan menunaikan kewajiban zakat. Artinya, jika seseorang menumpuk emas atau perak yang sudah mencapai nisab dan haul, namun ia enggan menunaikan zakat, maka itulah yang disebut iktinaz. Simak penjelasan lengkapnya:
فقال بعضهم : هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، فلم تؤد زكاته . قالوا : وعنى بقوله : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) ، ولا يؤدون زكاتها .
Artinya: “Sebagian ulama berkata: ‘Kanz/iktinaz adalah setiap harta yang wajib dizakati, tetapi zakatnya tidak dikeluarkan.’ Mereka menjelaskan maksud dari firman Allah Ta‘ala: ‘dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah’ yaitu, mereka tidak menunaikan zakatnya,” (Imam Thabari, Jamiul Bayan, (Mesir: Darul Ma’arif, tt) Jilid XIV, hlm. 217).
Menurut Imam Thabari, riwayat Ibnu Umar (tentang iktinaz) inilah yang paling kuat. Pandangan ini tentu ada konsekuensinya, bahwa harta yang ditimbun tetapi zakatnya sudah dikeluarkan, tidak termasuk kanz/iktinaz. Artinya, seseorang boleh saja menyimpan hartanya meski jumlahnya sangat banyak, asalkan kewajiban zakat sudah ditunaikan. Sebaliknya, jika zakatnya belum dibayar, pemiliknya tetap terkena ancaman siksa dari Allah. Jadi, inti larangan menimbun harta bukan soal jumlah, melainkan soal ketaatan pada kewajiban zakat.
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، القول الذي ذكر عن ابن عمر : من أن كل مال أديت زكاته فليس بكنز يحرم على صاحبه اكتنازه ، وإن كثر وأن كل مال لم تؤد زكاته فصاحبه معاقب مستحق وعيد الله، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل ، إذا كان مما يجب فيه الزكاة
Artinya; Abu Ja‘far berkata: “Pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah pendapat yang disebutkan dari Ibnu ‘Umar, yaitu: setiap harta yang zakatnya telah dikeluarkan bukanlah kanz, sehingga pemiliknya tidak terlarang untuk menimbunnya, meskipun banyak jumlahnya. Sedangkan setiap harta yang zakatnya belum ditunaikan, pemiliknya akan menerima siksa dan ancaman Allah, kecuali Allah berkenan memaafkannya, meskipun jumlahnya sedikit, selama harta itu wajib dizakati.” (Imam Thabari, Jamiul Bayan, Jilid XIV, hlm. 217).
Kedua, yang dimaksud iktinaz atau menimbun harta adalah seseorang yang memiliki harta yang melebihi ambang batas tertentu, yaitu 4.000 dirham. Menurut pendapat ini, Islam tidak hanya melihat iktinaz dari sisi apakah zakatnya telah dibayarkan atau tidak, tetapi dari sisi jumlah kepemilikan itu sendiri.
Selama seseorang memiliki harta di bawah 4.000 dirham, hal itu dianggap wajar dan masih dalam batas kebutuhan hidup. Namun, ketika kepemilikan melampaui angka tersebut, maka selisihnya dikategorikan sebagai iktinaz, yakni harta yang ditimbun.
Pendapat kedua ini berbeda dengan pandangan pertama yang dianggap sahih oleh Imam Thabari. Dalam pandangan ini, zakat tidak diperhitungkan. Artinya, meskipun zakat sudah dibayar, jika harta lebih dari 4.000 dirham, kelebihannya tetap disebut iktinaz (harta yang ditimbun).
Pada masa awal Islam, 4.000 dirham adalah jumlah yang sangat besar. Sebagai perbandingan, batas wajib zakat hanya 200 dirham, berarti 20 kali lipat dari kewajiban zakat. Begitu pula bila dihitung dengan upah seorang pekerja yang hanya mendapat 1–2 dirham per hari. Bahkan, gaji tahunan seorang pejabat atau prajurit sering kali tidak mencapai 1.000 dirham. Karena itu, 4.000 dirham setara dengan hasil kerja beberapa tahun orang kelas menengah. Jumlah ini dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak, termasuk rumah, pakaian, makanan, dan biaya keluarga.
Dalam konteks tersebut, memiliki harta di bawah 4.000 dirham masih dikategorikan wajar, yakni sebagai modal bertahan hidup (survival) atau jaminan keamanan ekonomi. Namun, ketika kepemilikan melampaui angka itu, selisihnya dinilai sebagai kelebihan yang tidak lagi berada di ranah kebutuhan, melainkan menjadi simbol akumulasi kekayaan. Di titik inilah istilah iktinaz diberlakukan. (Lihat: Imam An-Nawawi, Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim, [Kairo: Darus Salam, tt], Jilid VII, hlm. 57).
Imam Thabari berkata:
وقال آخرون : كل مال زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز أديت منه الزكاة أو لم تؤد
Artinya: “Dan yang lain berkata: ‘Setiap harta yang melebihi empat ribu dirham adalah kanz, baik zakatnya telah dikeluarkan maupun belum.’” (Imam Thabari, Jami‘ul Bayan, Jilid XIV, hlm. 217).
Ketiga, yang dimaksud iktinaz adalah setiap harta yang melebihi kebutuhan pemiliknya. Definisi ini memberikan pendekatan moral yang lebih mendasar. Menimbun harta tidak semata-mata diukur dari besarnya nominal atau apakah zakatnya telah dibayarkan atau belum. Tolok ukurnya adalah seberapa jauh harta tersebut berada di luar kebutuhan wajar pemiliknya.
Dengan kata lain, jika seseorang memiliki kekayaan lebih yang tidak digunakan untuk kebutuhan hidupnya, tidak disalurkan untuk kemaslahatan keluarga, masyarakat, atau kepentingan publik, maka kelebihan itu dianggap sebagai harta yang ditimbun.
Simak keterangan berikut:
وقال آخرون: “الكنز” كل ما فضل من المال عن حاجة صاحبه إليه
Artinya: Dan yang lain berkata: “Kanz adalah setiap harta yang melebihi kebutuhan pemiliknya.” (Imam Thabari, Jami‘ul Bayan, Jilid XIV, hlm. 217).
Pandangan serupa ditegaskan oleh ulama besar dari mazhab Hanafi, Ibnu ‘Abdil Barr. Dalam kitab al-Istidzkar, beliau menjelaskan bahwa menimbun harta bukan sekadar perkara tidak membayar zakat. Lebih jauh dari itu, menimbun harta berarti menahan harta melebihi kebutuhan sehingga menimbulkan kesulitan di tengah masyarakat.
Ia bahkan mengutip sikap tegas sahabat Nabi, Abu Dzar al-Ghifari:
Artinya, “Setiap harta yang melebihi kebutuhan pokok adalah harta yang ditimbun, dan ayat ancaman (At-Taubah: 34–35) diturunkan untuk itu.”
Menariknya, Ad-Dhahhak bin Muzahim, seorang ulama dari kalangan tabi‘in, memberikan ukuran yang lebih konkret. Ia berkata:
Artinya, “Siapa yang memiliki sepuluh ribu dirham termasuk orang yang paling banyak dan paling merugi, kecuali jika hartanya digunakan untuk menyambung silaturahmi, memberi tetangga, membantu yang lemah, dan sedekah.”
Artinya, iktinaz bukan diukur dari angka absolut, melainkan dari fungsi sosial kekayaan itu sendiri. Harta yang produktif dan mengalir ke masyarakat serta pasar untuk menggerakkan fungsi ekonomi tidak dianggap sebagai timbunan. Sebaliknya, harta yang hanya menjadi tumpukan pasif, walaupun legal dan telah dizakati, tetap dikategorikan sebagai iktinaz.
Kenapa Iktinaz (Menimbun Harta) Diharamkan dalam Islam?
Dalam perspektif ekonomi Islam, kekayaan memiliki fungsi sosial. Di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikan. Harta tidak boleh sekadar menjadi simbol prestise pribadi, melainkan harus menjadi sarana untuk membangun kemaslahatan bersama, antara lain melalui instrumen zakat, sedekah, dan wakaf.
Demikian pula dengan uang. Secara ideal, uang berfungsi sebagai alat tukar sekaligus penggerak aktivitas produksi. Namun, ketika uang berhenti berputar, roda ekonomi pun tersendat.
Penimbunan kekayaan dalam bentuk aset tidak produktif—baik berupa uang, komoditas, maupun properti, dapat menciptakan kelangkaan buatan (artificial scarcity). Fenomena inilah yang pada akhirnya menimbulkan distorsi ekonomi sekaligus menghambat tercapainya keadilan sosial.
Dampak Sosial dari Iktinaz (Menimbun Harta)
Lebih jauh lagi, akibat dari iktinaz atau menimbun harta, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil. Tidak bisa dipungkiri, akan terjadi kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok karena barang menjadi langka di pasaran. Ketika barang langka, harganya otomatis melonjak. Akibatnya, masyarakat dengan ekonomi lemah tidak mampu membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, atau obat-obatan.
Imbas lain yang tak kalah ironis adalah makin lebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Rasa keadilan dalam masyarakat pun terganggu. Orang bisa merasa bahwa aturan hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Jika dibiarkan, praktik ini berpotensi memicu kecemburuan sosial dan mengancam ketenteraman hidup bersama.
Apakah Islam Melarang Menabung atau Berinvestasi?
Setelah jelas imbas dari iktinaz, muncul pertanyaan lanjutan: “Kalau begitu, apakah Islam juga tidak membolehkan menabung atau berinvestasi untuk masa depan?”
Jawabannya tegas: Islam tidak melarang menabung. Bahkan, perencanaan finansial untuk kebutuhan masa depan anak dan keluarga merupakan bagian dari ajaran Islam. Tentu dengan catatan, hal itu dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melupakan kewajiban sosial.
Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menjelaskan, bahwa surat At-Taubah ayat 34 tidak mengecam semua orang yang mengumpulkan kekayaan, apalagi mereka yang menabung untuk kebutuhan masa depan. Kecaman Al-Qur’an secara spesifik ditujukan kepada mereka yang menghimpun harta tanpa mau menunaikan kewajiban di jalan Allah, seperti zakat dan sedekah. Selain itu, kecaman juga berlaku bagi orang yang sengaja memonopoli ekonomi sehingga menimbulkan ketidakstabilan. Inilah yang disebut sebagai iktinaz atau penimbunan harta (Prof. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, [Ciputat: Lentera Hati, 2002], Jilid V, hlm. 582).
Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam mengakui pentingnya kesiapan finansial dan kemandirian ekonomi umat. Yang menjadi masalah bukanlah keberadaan harta itu sendiri, melainkan sikap kikir. Selama kekayaan dialirkan untuk kemaslahatan bersama dan tidak sekadar disimpan untuk memperkuat ego pemiliknya, maka hal itu tidak termasuk dalam kategori iktinaz yang dikecam Al-Qur’an.
Ancaman Iktinaz dalam Al-Qur’an
Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan larangan menimbun harta (iktinaz atau kanz). Keterangan berikut menjelaskan ancaman bagi mereka yang tetap bersikukuh dalam praktik menimbun kekayaan.
Ibnu ‘Abdil Barr dalam al-Istidzkar menegaskan bahwa Islam mengecam keras perilaku tamak ini. Beliau mengutip sebuah riwayat dari Abu Dzar al-Ghifari, sahabat Nabi yang terkenal lugas, mengenai siksaan bagi para penimbun harta. Ia berkata bahwa kelak di akhirat harta itu akan ditempelkan dengan besi panas pada tubuh mereka sebagai bentuk azab yang pedih.
وكان أبو ذر يقول : بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور
Artinya: Dan Abu Dzar berkata: “Sampaikanlah kabar kepada para pemilik harta timbunan (kanz) dengan azab berupa ditempelkan besi panas pada dahi mereka, pada sisi tubuh mereka, dan pada punggung mereka.” (Ibnu Abdil Bar, Al-Istidzkar, [Beirut: Darul Qutaibah, 1993 M], Jilid IX, hlm, 119).
Lebih jauh, Ibnu Mas‘ud menggambarkan ancaman itu dengan lebih detail. Menurut beliau, Allah tidak menghitung dosa satu per satu, tidak dinar demi dinar, tidak pula dirham demi dirham. Sebaliknya, kulit pelakunya akan dilebarkan, lalu setiap keping harta itu ditempelkan ke tubuhnya sebagai siksaan.
Sejatinya, gambaran siksaan ini merupakan peringatan keras bagi manusia yang hidup di dunia hari ini. Pada dasarnya, harta dapat menjadi penyelamat bila dibagikan. Namun, di sisi lain, harta juga bisa berubah menjadi hukuman bila ditimbun. Karena itu, sebelum harta berubah menjadi bara, lebih baik ia disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.
عن ابن [ ص: 122 ] مسعود قال : والذي لا إله غيره لا يعذب رجل يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته
Artinya: Dari Ibn Mas’ud, ia berkata: “Demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia, Allah tidak akan mengazab seseorang yang menimbun harta lalu setiap dinar dan dirham menempel satu per satu pada kulitnya. Tetapi, Allah akan melebarkan kulitnya hingga setiap dinar dan dirham bisa sampai kepadanya satu per satu.”
Sementara itu, masih terkait dengan siksa bagi mereka yang tetap melanggengkan penimbunan harta, Prof. Quraish Shihab menjelaskan bahwa siksaan itu akan menimpa para penghimpun harta yang enggan menafkahkannya di jalan Allah. Dalam ayat di atas, siksa tersebut digambarkan mengenai tiga bagian tubuh: dahi, lambung, dan punggung.
Mengapa bagian-bagian ini disebut secara khusus? Mengutip pendapat Asy-Sya’rawi, Prof. Quraish Shihab menegaskan bahwa setiap bagian tubuh tersebut berperan dalam lahirnya sifat kikir. Dahi adalah bagian yang pertama kali bereaksi ketika seseorang datang meminta bantuan.
Orang yang kikir biasanya langsung memalingkan wajah atau mengernyitkan dahi sebagai tanda ketidaksukaan. Sikap ini saja sudah cukup membuat peminta merasa terhina. Jika peminta tetap bertahan, orang yang kikir akan memalingkan badannya, seolah ingin mengabaikan. Dan bila permintaan masih dilanjutkan, ia mengambil langkah terakhir dengan membelakangi dan pergi meninggalkan orang yang membutuhkan.
Tahapan sikap ini, dari dahi, badan, hingga punggung, menunjukkan betapa kuatnya rasa enggan berbagi. Maka tidak mengherankan bila kelak ketiga bagian tubuh ini menjadi tempat datangnya siksa. Tubuh yang dahulu dipakai untuk menolak, akan menjadi saksi dan objek balasan. (Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, [Ciputat: Lentera Hati, 2002], Jilid V, hlm. 582).
Ayat ini menyampaikan pesan penting: harta yang tidak digunakan untuk kemaslahatan, kelak justru menjadi jerat bagi pemiliknya. Dalam konteks modern, sifat iktinaz atau penimbunan harta tidak lagi hanya berbentuk emas dan perak yang disembunyikan. Ia dapat hadir dalam rupa rekening yang terus membengkak tanpa kebermanfaatan, aset yang dibiarkan tidak produktif, hingga praktik monopoli yang menutup akses bagi orang lain.
Baca juga: Kisah Nabi Yusya’ bin Nun Lengkap
Karena itu, Al-Qur’an melarang penimbunan harta dan menuntut agar kekayaan terus berputar demi terciptanya keadilan sosial. Harta yang dibagikan akan menjadi pelindung, tetapi harta yang ditahan akan berubah menjadi ancaman. Pertanyaannya kini sederhana: apakah kekayaan yang kita miliki sedang kita rawat, atau justru diam-diam sedang merawat siksa bagi diri kita sendiri?
Sumber: islam.nu.or.id